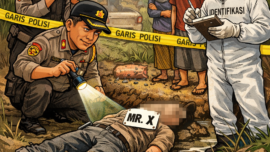JAKARTA, ifakta.co – Genap berusia 498 tahun, Jakarta bukan sekadar ibu kota negara, melainkan sebuah entitas sejarah, sosial, dan ekonomi yang membentuk wajah Indonesia modern.
Di balik gegap gempita ulang tahun ke-498 ini, Jakarta berdiri di titik kritis. Antara kejayaan masa lalu dan tantangan masa depan, kota ini menyimpan jejak perubahan yang dramatis dan kadang kontradiktif.
Dari Sunda Kelapa ke Jakarta
Iklan
Awal mula Jakarta tercatat dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, yang menjadi pusat perdagangan Kerajaan Sunda Pajajaran. Pada 22 Juni 1527, Fatahillah dari Kesultanan Demak merebut pelabuhan ini dari Portugis dan menamainya Jayakarta. Tanggal inilah yang kelak dijadikan tonggak hari lahir Jakarta.
Kemudian, VOC Belanda menghancurkan Jayakarta pada 1619 dan membangun Batavia sebagai pusat kekuasaan kolonial. Batavia menjadi cikal bakal kota metropolitan, meski dibangun di atas ketimpangan rasial dan sosial. Setelah Indonesia merdeka, nama Batavia diganti menjadi Jakarta dan diresmikan sebagai ibu kota Republik.
Budaya yang Bertahan di Tengah Deru Mesin Kota
Di tengah urbanisasi masif, Jakarta masih menyisakan denyut budaya Betawi. Gambang kromong, lenong, dan ondel-ondel tetap menjadi simbol perlawanan terhadap arus modernisasi yang menggulung identitas lokal.
“Jakarta boleh berubah jadi kota global, tapi jangan pernah hilangkan napas budayanya,” ujar Ratna Kurniasih, budayawan dari Setu Babakan. “Ondel-ondel, lenong, tanjidor itu bukan sekadar hiburan, tapi identitas.”
Namun budaya Betawi makin terdesak. Warga asli tergusur oleh pembangunan, lahan budaya direduksi menjadi festival tahunan. Tanpa keberpihakan kebijakan yang serius, Jakarta bisa kehilangan jiwanya.
Sejak masa kolonial, Jakarta adalah panggung kekuasaan. Dari Soekarno hingga Joko Widodo, dari Ali Sadikin hingga Anies Baswedan, Jakarta menjadi tempat bertarungnya ideologi dan kebijakan. Posisi gubernur DKI bahkan sering dianggap sebagai batu loncatan menuju jabatan nasional.
“Jakarta selalu jadi cermin kekuasaan. Siapa yang berhasil memimpin Jakarta dengan baik, punya panggung terbuka ke arah yang lebih tinggi,” kata Prof. Dr. Yusril Djamaluddin, pengamat politik UI.
Namun kekuasaan juga menghadirkan dilema. Penertiban, reklamasi, dan penggusuran kerap membuat pemerintah daerah terjebak antara pembangunan dan keadilan sosial.
Ekonomi yang Tumbuh, Tapi Tidak Merata
Jakarta menyumbang lebih dari 17% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Kawasan Sudirman, Kuningan, dan SCBD menjelma sebagai pusat bisnis Asia Tenggara. Tapi gemerlap ekonomi ini berbanding terbalik dengan wajah Jakarta yang lain: kampung-kampung padat, ketimpangan sosial, dan pekerja informal yang terpinggirkan.
“Ekonomi Jakarta memang tumbuh, tapi tidak semua warganya tumbuh bersama. Ketimpangan adalah bom waktu,” tegas Dian Permata, ekonom dari Urban Institute.
Ribuan pedagang kaki lima, buruh harian, dan ojek daring menopang aktivitas harian kota. Namun mereka sering absen dalam kebijakan ekonomi daerah.
Lingkungan, Kemacetan, dan Kaum Urban Penyangga
Jakarta menghadapi tekanan ekologis yang luar biasa. Polusi udara memburuk, kemacetan makin parah, dan volume sampah harian mencapai 7.500 ton. Kota ini tidak berdiri sendiri; setiap hari jutaan kaum urban dari Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang masuk ke Jakarta.
“Jakarta siang hari bisa berpenduduk 14 juta jiwa. Tapi malamnya kembali jadi 10 jutaan. Artinya, kota ini memikul beban yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh APBD-nya,” ungkap Dede Yusuf, anggota DPR RI.
Kemacetan dan ketergantungan pada kendaraan pribadi menjadi krisis harian. MRT, LRT, dan TransJakarta memang membantu, tapi belum menyentuh semua titik. Transportasi lintas wilayah belum sepenuhnya terintegrasi.
Perubahan Iklim, Banjir, dan Tata Ruang Masa Depan
Perubahan iklim makin memperparah krisis Jakarta. Banjir musiman, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan laut mengancam wilayah pesisir. Ancol, Muara Baru, dan Penjaringan adalah kawasan paling rentan.
“Jakarta bisa tenggelam sebagian dalam 20-30 tahun ke depan kalau tak ada intervensi serius,” kata Dr. Arif Wibowo, pakar tata ruang dari ITB.
Program normalisasi dan naturalisasi sungai masih belum cukup. Di sisi lain, reklamasi dan ekspansi permukiman pesisir justru memperparah kerentanan.
Jakarta butuh visi baru tata ruang. Kota ini harus menyeimbangkan fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis. Setelah tak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta harus menemukan perannya sebagai kota global yang tangguh iklim dan manusiawi.
“Jakarta tidak akan pernah benar-benar nyaman kalau Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang tidak ikut maju bersama,” kata Nani Suryani, Direktur Jakarta Urban Reform.
Refleksi di Usia 498
Di usia yang ke-498 ini, Jakarta sedang menata arah baru. Ia bukan lagi sekadar ibu kota, tapi wajah Indonesia di mata dunia. Kota ini memikul beban sejarah dan harapan masa depan. Apakah Jakarta bisa menjadi kota yang setara, berkelanjutan, dan beradab? Atau hanya akan terus menjadi medan pertarungan antara kapital dan rakyat?
Jawabannya ada pada kita semua: pengambil kebijakan, pelaku budaya, kelas menengah, dan kaum urban yang menjejaki trotoar-trotoar ibu kota setiap hari.
(my/my)