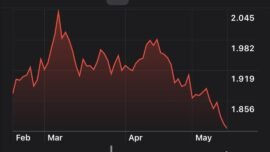JAKARTA, ifakta.co – Novel Broken Strings karya Aurelie Moeremans menjadi perhatian luas publik setelah sang penulis mengungkap bahwa cerita di dalamnya berangkat dari pengalaman nyata hidupnya. Bagi Aurelie, buku tersebut bukan hanya karya sastra, melainkan medium kejujuran sekaligus keberanian untuk membuka luka masa lalu yang selama ini tersimpan dalam diam.
Melalui Broken Strings, Aurelie menuturkan pengalaman pahitnya sebagai korban child grooming hingga kekerasan seksual di usia muda. Narasi yang disajikan menggambarkan bagaimana pelaku memanfaatkan relasi kuasa untuk membangun manipulasi secara perlahan, menjerat korban dalam hubungan yang tampak normal, tetapi sejatinya penuh tekanan dan eksploitasi.
Kisah ini menegaskan bahwa apa yang dialami korban bukan relasi suka sama suka, melainkan tindak kejahatan yang merampas rasa aman dan hak korban.
Iklan
Novel tersebut juga menyoroti bagaimana korban kerap berada dalam situasi terbungkam. Pola child grooming bekerja melalui pendekatan halus dan manipulatif, membuat korban sulit mengenali kekerasan yang dialaminya, apalagi berani bersuara. Ketimpangan relasi kuasa semakin memperparah kondisi tersebut, menempatkan korban pada posisi yang sangat rentan.
Aktivis perempuan sekaligus pendiri Women’s March Malang, Reni Eka Mardiana, menilai isu child grooming dan kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Menurutnya, fenomena ini ibarat gunung es, di mana kasus yang terungkap hanya sebagian kecil dari kenyataan yang ada.
“Kasus-kasus seperti ini kini juga marak terjadi di ruang digital. Ini persoalan struktural yang harus terus disuarakan,” ujar Reni, yang akrab disapa Rere.
Ia menjelaskan, kuatnya budaya patriarki, normalisasi kontrol atas tubuh perempuan dan anak, serta ketimpangan relasi kuasa menjadi faktor utama mengapa kekerasan seksual terus berulang. Karena itu, kisah-kisah seperti yang diangkat Aurelie perlu dibuka ke ruang publik agar tidak kembali terjadi di masa depan.
Dari sisi hukum, Rere menilai sistem perlindungan di Indonesia belum sepenuhnya berpihak pada korban. Penegakan hukum masih berfokus pada pembuktian fisik, sementara dalam kasus child grooming, kekerasan lebih banyak terjadi secara psikologis melalui manipulasi bertahap. Proses hukum pun kerap menempatkan korban pada situasi yang memberatkan, mulai dari pertanyaan yang menyudutkan, praktik victim blaming, hingga risiko retraumatisasi.
Menurut Rere, pemulihan korban kekerasan seksual membutuhkan waktu yang panjang dan berbeda bagi setiap individu. Dalam perspektif feminis, pemulihan tidak diartikan sebagai kembali ke kondisi sebelum trauma, melainkan sebagai proses merebut kembali kendali atas hidup.
“Pulih itu bukan soal melupakan, tapi bagaimana korban bisa mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri tanpa terus dibayangi trauma,” tuturnya.
Proses pemulihan, lanjut Rere, memerlukan dukungan banyak pihak, mulai dari lingkungan yang aman dan suportif hingga pendampingan profesional seperti terapis. Dalam konteks Aurelie, kesadaran bahwa apa yang dialaminya merupakan bentuk kekerasan menjadi titik awal untuk keluar dari relasi yang manipulatif, meskipun jalan menuju pemulihan tidaklah mudah.
Trauma, menurut Rere, memang tidak sepenuhnya hilang, tetapi dapat diolah dan diintegrasikan dalam kehidupan. Aurelie memilih menghadapi dan mengolah lukanya, sehingga trauma tersebut tidak lagi sepenuhnya menguasai hidupnya.
Melalui Broken Strings, Aurelie Moeremans menyampaikan pesan penting tentang arti mendengarkan suara korban sebagai langkah awal menuju keadilan. Masyarakat diingatkan agar tidak menutup mata terhadap kondisi para penyintas kekerasan seksual, serta mendorong perubahan budaya, sosial, dan hukum yang lebih berpihak pada korban.
Buku ini juga menjadi ruang harapan bagi penyintas lain untuk berani bersuara. Kehadiran kisah Aurelie membuka kesadaran bahwa kekerasan seksual dan child grooming adalah lingkaran trauma yang nyata, terutama bagi perempuan.
“Ada publik figur yang berada dalam posisi rentan seperti ini. Aurelie seolah memberi ruang bagi penyintas lain untuk ikut bersuara,” pungkas Rere.
(naf/kho)