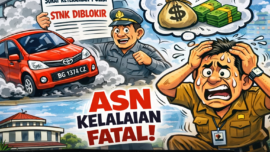JAKARTA, ifakta.co | Nyai Dasimah adalah sosok perempuan pribumi yang kisahnya menjadi simbol dilema perempuan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Namanya dikenal luas melalui karya sastra populer berjudul Tjerita Njai Dasima (1896) karya G. Francis, yang kemudian diadaptasi dalam berbagai versi, termasuk film dan sandiwara. Cerita ini mencerminkan ketegangan sosial, budaya, dan identitas yang dihadapi oleh perempuan pribumi, terutama mereka yang menjadi “nyai” sebutan bagi perempuan Indonesia yang menjadi selir atau istri tidak resmi bagi pria Eropa.
Nyai Dasimah digambarkan sebagai perempuan cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga baik-baik. Ia menjalin hubungan dengan seorang pria Belanda dan hidup berkecukupan. Namun, di balik kemewahan itu, Dasimah merasa terasing dari akar budayanya dan mengalami krisis identitas. Dalam cerita, Dasimah akhirnya meninggalkan pasangannya dan mencoba kembali ke masyarakat pribumi, namun justru dikhianati dan dibunuh oleh orang yang dipercayainya.
Cerita ini mengangkat berbagai tema penting: subordinasi perempuan, konflik budaya Timur dan Barat, serta pertentangan antara status sosial dan kehendak pribadi. Nyai Dasimah tidak hanya menjadi tokoh fiktif, tetapi juga mewakili suara perempuan yang terpinggirkan dalam sistem kolonial.
Iklan
Istilah “nyai” pada zaman kolonial seringkali memiliki konotasi negatif, karena banyak dari mereka dianggap sekadar pelengkap hidup pria Belanda. Namun, kisah Nyai Dasimah membuka wacana bahwa para nyai bukan sekadar korban, tetapi juga pelaku sejarah yang memiliki pilihan dan perasaan. Mereka menghadapi diskriminasi dari dua sisi: dari penjajah dan dari masyarakatnya sendiri.
Melalui figur Nyai Dasimah, kita bisa melihat bagaimana sistem kolonial menempatkan perempuan dalam posisi serba salah mereka bisa mendapatkan pendidikan dan kemewahan dari dunia Barat, tetapi di saat yang sama harus menanggung stigma dan kehilangan tempat dalam masyarakat tradisional.
Kisah Nyai Dasimah telah diadaptasi ke dalam berbagai bentuk : film era 1929, 1932, 1940, dan versi yang lebih modern. Ia menjadi ikon yang terus dikenang karena kisahnya tetap relevan dengan isu-isu perempuan hingga saat ini : kebebasan memilih, hak atas tubuh, serta perjuangan menghadapi stereotip dan diskriminasi. (FA)